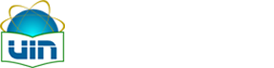Mengapa Rebranding ‘Department of War’ AS Dapat Mengancam Keamanan Dunia
Penulis : Dira Natasya, mahasiswa Hubungan Internasional
Dari “Pertahanan” ke “Perang” sebagai Tanda Bahaya bagi Keamanan Internasional
Dalam beberapa waktu terakhir muncul wacana dari Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanannya Pete Hegseth, untuk mengganti nama Department of Defense (DoD) Amerika Serikat menjadi Department of War. Sekilas usulan ini terlihat hanya sekadar rebranding institusi militer. Namun di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan rentannya tatanan keamanan global, perubahan ini justru mencerminkan pergeseran cara pandang Amerika terhadap perang dan perdamaian.
Perubahan nama ini bukan sekadar masalah perubahan kata namun juga perubahan makna yang mengandung pesan politik. Trump bahkan secara terbuka mengatakan, “Defense is too defensive. And we want to be defensive, but we want to be offensive too, if we have to be.” Kutipan ini menunjukkan bahwa niat di balik perubahan tersebut bukan hanya soal citra, melainkan orientasi strategis dimana Trump ingin agar Amerika Serikat kembali dipandang sebagai kekuatan ofensif, bukan defensif. Dalam konteks keamanan internasional, hal ini berpotensi menciptakan ketegangan baru dan memperburuk instabilitas global.
Dari “Pertahanan” ke “Perang” sebagai Pergeseran Makna dan Niat
Secara historis Department of War memang pernah menjadi nama resmi lembaga militer Amerika sejak awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Nama itu digunakan selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, ketika orientasi militer Amerika benar-benar berpusat pada mobilisasi perang global. Baru pada tahun 1949, Presiden Harry S. Truman menggantinya menjadi Department of Defense untuk menegaskan semangat pencegahan konflik dan orientasi defensif pasca tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern.
Perubahan itu bukan sekadar administrasi, tapi juga refleksi moral. Dunia baru saja menyaksikan pembantaian massal, bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta krisis kemanusiaan yang tak terbayangkan. Maka istilah “pertahanan” dipilih sebagai simbol dari tekad baru: militer Amerika ada untuk melindungi, bukan memulai perang.
Kini di bawah wacana politik Trump dan Hegseth semangat itu tampak bergeser. Mereka mendorong pengembalian nama lama bukan karena alasan sejarah semata, melainkan untuk menegaskan kembali karakter militer yang ofensif. Dalam wawancara Fox News, Hegseth bahkan menyatakan bahwa ia ingin para prajurit AS “benar-benar memahami cara berperang dan mengerti cara melakukan pembunuhan terhadap musuh.”
Pernyataan semacam itu menggambarkan orientasi militeristik yang menormalisasi kekerasan dan mengagungkan agresi sebagai ciri kekuatan nasional. Tak heran bila seorang pejabat Pentagon kemudian memperingatkan bahwa langkah ini dapat membuat musuh-musuh AS menganggap Amerika sebagai “penghasut perang” dan ancaman bagi stabilitas global.
Simbol yang Mengubah Persepsi Dunia
Dalam teori hubungan internasional khususnya pendekatan constructivism, bahasa dan simbol bukan sekadar alat komunikasi, melainkan unsur yang membentuk identitas dan perilaku negara. Perubahan dari defense menjadi war menandakan transformasi identitas strategis AS dari kekuatan yang menekankan perlindungan menjadi kekuatan yang menormalisasi agresi.
Pertama, secara simbolik istilah “war” menggeser narasi moral AS dari pelindung tatanan dunia menuju aktor yang menilai kekerasan sebagai keniscayaan. Ini memperkuat military-first mentality, di mana diplomasi dan multilateralisme semakin tersingkir dari prioritas kebijakan luar negeri.
Kedua, perubahan persepsi ini akan memengaruhi kalkulasi geopolitik global. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran kemungkinan akan menafsirkan langkah ini sebagai sinyal intensi ofensif. Dalam konteks security dilemma, persepsi ancaman seperti ini mendorong negara lain memperkuat militernya, meningkatkan perlombaan senjata, dan mempersempit ruang bagi diplomasi. Akibatnya, stabilitas internasional menjadi semakin rapuh.
Ketiga, perubahan ini juga mengandung dimensi etis. Ketika seorang Menteri Pertahanan berbicara terbuka tentang pentingnya “mengerti cara membunuh musuh,” pesan yang tersampaikan bukan lagi soal kehormatan profesi militer, tetapi normalisasi kekerasan. Ini bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan internasional dan prinsip just war theory yang selama puluhan tahun menjadi landasan etika perang modern.
Selain itu, langkah ini juga bisa memperlemah legitimasi moral Amerika sendiri. Selama ini, Amerika selalu menempatkan dirinya sebagai penjaga demokrasi dan perdamaian dunia. Tapi jika simbol resminya adalah “Departemen Perang,” bagaimana mereka bisa meyakinkan dunia bahwa setiap intervensinya dilakukan demi perdamaian, bukan ambisi?
Amerika dan Kembalinya Politik Kekuatan
Jika kita membaca arah ini secara strategis, terlihat jelas bahwa usulan tersebut bukan hanya soal nama, tetapi tentang bagaimana Amerika ingin dipersepsikan oleh dunia. Di satu sisi Trump dan Hegseth mungkin ingin menampilkan AS sebagai negara yang “jujur” dengan kekuatan militernya. Namun di sisi lain, kejujuran tanpa tanggung jawab justru menjadi preseden berbahaya bagi sistem internasional.
Sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia dan pengaruh hegemonik yang luas, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas global. Mengganti “pertahanan” dengan “perang” justru mengaburkan komitmen tersebut. Dunia tidak membutuhkan pemimpin yang bangga dengan kemampuan perang, tetapi pemimpin yang mampu menahan diri dari menggunakannya.
Bila perubahan ini benar-benar dilakukan, ia akan memperkuat citra AS sebagai kekuatan agresif bukan penjaga tatanan dunia, melainkan ancaman terhadapnya. Dalam konteks keamanan internasional, langkah ini menciptakan risiko misperception, memperburuk polarisasi global, dan mendorong lahirnya kembali politik kekuatan yang mengedepankan ancaman dan kekerasan.
Perubahan nama Department of Defense menjadi Department of War mungkin terlihat simbolik, tetapi dalam politik internasional, simbol membentuk persepsi, dan persepsi membentuk kebijakan. Ketika simbol pertahanan digantikan oleh simbol perang, dunia akan menafsirkan bahwa Amerika telah memilih jalan konfrontatif. Saya pribadi memandang isu ini sebagai ancaman nyata terhadap keamanan internasional. Karena jika Amerika Serikat benar-benar ingin menjaga tatanan dunia yang stabil, maka narasi perang seharusnya tak kembali menjadi identitas resmi pertahanannya.
Kritik atas Arah Militeristik Amerika
Kalau saya melihatnya secara pribadi, ide untuk mengganti Department of Defense menjadi Department of War justru menunjukkan bagaimana sebagian elit politik AS gagal belajar dari sejarah. Mereka mengira dengan memperlihatkan wajah yang lebih agresif, Amerika akan kembali disegani. Padahal, di dunia sekarang, kekuatan bukan hanya soal seberapa besar arsenal senjata, tapi seberapa besar pengaruh moral dan kepercayaan yang dimiliki.
Bagi saya, orientasi militeristik ini sangat berbahaya bagi keamanan internasional. Amerika adalah aktor global yang punya pengaruh luar biasa besar. Setiap perubahan dalam kebijakan dan retorika militernya punya efek berantai ke seluruh dunia. Saat mereka berbicara tentang “perang,” negara lain tidak akan melihat itu sebagai simbol semangat juang, melainkan ancaman langsung.
Lebih dari itu, retorika seperti ini juga mempersempit ruang diplomasi. Kalau negara terkuat di dunia saja mengedepankan “perang” dalam identitas resminya, lalu bagaimana dengan negara-negara yang lebih kecil? Apakah mereka tidak akan ikut merasa perlu memperkuat diri? Ini bukan hanya soal nama, tapi soal pesan yang dikirim ke dunia: bahwa kekuatan militer adalah bahasa utama hubungan internasional.
Menurut saya, langkah ini juga menunjukkan bahwa AS sedang kehilangan kepercayaan diri terhadap kekuatan ide dan diplomasi. Dulu, dunia menaruh hormat pada Amerika bukan karena mereka punya senjata paling canggih, tapi karena mereka bisa meyakinkan negara lain lewat nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tatanan berbasis aturan. Sekarang, nilai-nilai itu semakin kabur di balik slogan-slogan agresif dan glorifikasi perang.
Kalau benar tujuan mereka adalah “menjaga keamanan,” maka yang dibutuhkan bukan nama baru, tapi cara pandang baru terhadap keamanan itu sendiri. Keamanan seharusnya berarti memberi rasa aman, bukan menakuti. Keamanan tidak hanya diukur dari jumlah kapal perang, tapi dari kemampuan negara membangun stabilitas tanpa senjata.
Bagi dunia, sinyal militeristik dari Amerika ini bisa menjadi pemicu instabilitas yang baru. Negara-negara yang selama ini bersikap netral bisa mulai mencari perlindungan ke blok lain, sementara sekutu-sekutu lama seperti Jepang dan Jerman mungkin mulai mempertanyakan arah kebijakan pertahanan mereka. Semua ini pada akhirnya membuat dunia semakin terpecah, bukan semakin aman.
Saya khawatir, kalau wacana ini benar-benar diwujudkan, maka dunia akan melihat kembalinya Amerika yang lebih mirip era Perang Dingin, negara yang siap menantang siapa pun, kapan pun, dengan keyakinan bahwa perang adalah solusi yang sah. Padahal seharusnya kita sudah melangkah jauh dari sana. Kalau Amerika benar-benar ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, ia harus sadar bahwa kepemimpinan tidak lahir dari ketakutan, tapi dari kepercayaan. Dunia tidak butuh Amerika yang “siap berperang,” dunia butuh Amerika yang mampu menahan diri.
Saya melihat wacana perubahan ini bukan hanya ancaman bagi tatanan global, tapi juga bagi masa depan moral politik dunia. Karena kalau negara yang paling berpengaruh di dunia mulai menormalisasi “perang” sebagai identitas resminya, maka dunia akan kehilangan arah moralnya. Dan pada akhirnya, jika Amerika benar-benar ingin menjaga tatanan dunia yang stabil, maka narasi perang seharusnya tidak kembali menjadi identitas resmi pertahanannya. Dunia tidak perlu lebih banyak perang, dunia butuh lebih banyak kebijaksanaan.