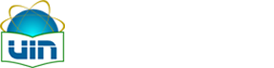Ketika Pertahanan Kembali Disebut Perang Refleksi atas Arah Baru Keamanan Amerika dan Dunia
Penulis : Bima Taqwa Satia Permana (Mahasiswa Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta)
Bahasa sering kali menjadi penanda arah dari perubahan itu sendiri. Amerika Serikat, melalui sebuah executive order pada September 2025, mengizinkan penggunaan kembali istilah “Department of War” sebagai secondary title bagi Departemen Pertahanan. Reaksi dunia tidak hanya muncul dari kalangan politik, tetapi juga dari para pengamat keamanan internasional, akademisi hubungan internasional, hingga aktivis perdamaian.
Meski kebijakan tersebut tampak administratif dan simbolik, gema sejarahnya mengguncang: sebuah kilas balik pada masa ketika “perang” bukan sekadar kata, melainkan cara pandang terhadap dunia. Ketika “pertahanan” berganti menjadi “perang,” bahkan jika hanya dalam ranah simbolik, maknanya tidak pernah netral. Ia membawa pesan tentang bagaimana suatu negara ingin memandang dirinya dan bagaimana dunia diminta untuk memandangnya kembali.
Sebuah Pergeseran Filosofis Dari War ke Defense
Sejarah panjang lembaga militer Amerika mencerminkan evolusi cara pandang terhadap kekuatan dan keamanan. Pada 1789, pemerintah federal mendirikan Department of War, yang bertugas mengelola urusan militer dan strategi pertahanan pascakemerdekaan. Dalam konteks abad ke-18, istilah war dianggap wajar karena negara muda itu masih berjuang menegakkan kedaulatan di dunia yang penuh konflik.
Namun, setelah Perang Dunia II, dunia memasuki fase baru yang menuntut keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi. Melalui National Security Act of 1947, Amerika membentuk National Military Establishment, yang dua tahun kemudian berganti nama menjadi Department of Defense (DoD). Pergantian ini bukan hanya kosmetik administratif, tetapi juga pernyataan politik global bahwa Amerika Serikat ingin menampilkan militernya sebagai penjaga stabilitas dunia, bukan pengobar perang.
Sebagaimana dicatat oleh Defense.gov (2024), transformasi itu adalah bagian dari pembentukan tatanan dunia liberal pasca-1945, di mana keamanan diposisikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan dominasi unilateral. Maka, ketika pada abad ke-21 istilah “Department of War” kembali dihidupkan, banyak pihak membaca sinyal adanya pergeseran: dari semangat pertahanan menuju penegasan kekuatan koersif.
Bahasa dan Kekuasaan Makna yang Melampaui Kata
Bahasa politik tidak pernah bebas nilai. Dalam politik luar negeri, istilah menjadi soft signal yang merefleksikan orientasi strategis. Kata war memanggil asosiasi tentang ofensif, dominasi, dan kekuatan koersif, sedangkan defense menandakan legitimasi, moralitas, dan hak membela diri.
Ketika negara sebesar Amerika menggunakan kembali istilah war, muncul pertanyaan: apakah ini sekadar romantisme historis, atau penegasan ideologis bahwa kekuatan keras (hard power) kembali menjadi pusat kebijakan luar negeri?
Simbol sering kali mendahului tindakan. Dalam sejarah, kata-kata telah membentuk doktrin: istilah containment pada masa Truman membentuk kebijakan global Amerika selama lebih dari empat dekade. Kini, kata war yang dihidupkan kembali dapat dibaca sebagai persiapan psikologis untuk menghadapi kompetisi strategis dengan Tiongkok dan Rusia dua kekuatan besar yang menantang dominasi Washington di Indo-Pasifik dan Eropa Timur.
Respons Dunia Antara Kekhawatiran dan Kewaspadaan
Sekutu Barat
Negara-negara Eropa Barat dan anggota NATO menanggapi keputusan ini dengan hati-hati. Walau belum ada perubahan struktural pada Pentagon, muncul kekhawatiran bahwa retorika “perang” bisa menggeser semangat pertahanan kolektif menjadi konfrontasi terbuka.
Di London dan Berlin, sejumlah pejabat pertahanan menyatakan bahwa perubahan simbolik ini “berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap stabilitas global” (BBC Europe, 2025). Dalam kerangka teori Kenneth Waltz (Theory of International Politics, 1979), persepsi terhadap ancaman sering kali lebih penting daripada ancaman itu sendiri, dan perubahan bahasa semacam ini dapat memicu reaksi berantai yang memperbesar security dilemma antarnegara.
Tiongkok dan Rusia
Bagi Beijing dan Moskow, kebijakan ini menjadi alasan tambahan untuk memperkuat narasi bahwa Amerika kembali ke politik kekuatan. Tiongkok melalui Global Times (Oktober 2025) menulis bahwa “penggunaan istilah war hanyalah pembenaran bagi kebijakan militerisasi Indo-Pasifik.” Rusia menanggapinya dengan retorika sinis: “Jika Washington menyebut dirinya Departemen Perang, kami akan memperkuat pertahanan kami dengan nama yang sama,” ujar Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dalam wawancara di RT News (2025).
Kedua negara memandang istilah itu sebagai legitimasi simbolik bagi AS untuk memperluas kekuatan militer di wilayah strategis seperti Laut Cina Selatan dan Eropa Timur wilayah yang menjadi garis depan ketegangan geopolitik global.
Global South
Negara-negara Selatan Global, termasuk India, Brasil, dan Indonesia, cenderung memandang langkah ini dengan keprihatinan pragmatis. Mereka menilai bahwa perubahan simbolik ini berpotensi memperkeras polarisasi global dan menggeser fokus dunia dari kerja sama pembangunan menuju perlombaan kekuatan militer baru. Dalam KTT Non-Blok (NAM) di Nairobi (2025), perwakilan India menekankan bahwa “simbolisme perang, di era krisis iklim dan kemiskinan global, adalah langkah mundur dari semangat multilateralisme.”
Antara Hukum Internasional dan Etika Global
Piagam PBB Pasal 2(4) menegaskan larangan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial negara lain, sementara Pasal 51 memberikan hak pertahanan diri. Dalam kerangka hukum ini, istilah defense memiliki legitimasi moral dan yuridis, sedangkan war menimbulkan dilema interpretatif.
Kata war mengandaikan ofensif, sedangkan defense menandai reaksi terhadap ancaman. Pergeseran semantik ini dapat memengaruhi interpretive framework terhadap legalitas intervensi militer. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa bahasa menjadi dasar legitimasi tindakan. Invasi Irak 2003 dilakukan atas dasar “pertahanan dari ancaman senjata pemusnah massal” namun hingga kini keabsahan moralnya masih diperdebatkan (Brookings Institution, 2023).
Dalam konteks serupa, jika istilah “war” diresmikan kembali, ia dapat membuka pintu bagi interpretasi agresif terhadap jus ad bellum hak untuk berperang yang seharusnya telah diredam dalam era hukum internasional modern. Etika global juga menuntut agar negara besar bertindak proporsional dengan kekuatannya. RAND Corporation (2024) menyebut bahwa “dominasi militer tanpa keseimbangan moral hanya akan menciptakan ketidakstabilan jangka panjang.” Maka, dunia kini menanti apakah Amerika mampu membuktikan bahwa simbolisme war tidak berubah menjadi kebijakan koersif.
Politik Domestik Antara Retorika dan Realitas
Di sisi domestik, keputusan ini dibaca sebagian pengamat sebagai strategi politik elektoral. Presiden Donald Trump dalam kampanye 2024 menegaskan bahwa “Amerika harus kembali menjadi bangsa yang berani berperang untuk melindungi kebebasannya.” Retorika semacam itu disambut positif oleh kelompok konservatif dan veteran militer, tetapi dikritik oleh kalangan Demokrat dan kelompok progressive pacifists yang menilai kebijakan ini berpotensi memicu ketegangan internasional.
Menurut survei Pew Research Center (September 2025), 58% warga AS mendukung penggunaan istilah “Department of War” karena dianggap menunjukkan ketegasan nasional, namun 35% menilai kebijakan itu “mengancam perdamaian dunia.” Dengan demikian, isu ini juga menjadi cermin polarisasi politik domestik di mana simbol kebijakan luar negeri digunakan sebagai alat mobilisasi nasionalisme dalam negeri.
Bahasa sebagai Cermin Kekuasaan
Dalam relasi antarnegara, istilah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan refleksi dari orientasi strategis dan psikologis suatu bangsa. Ketika istilah “war” kembali digunakan, dunia seolah diajak mengingat masa ketika perang dianggap solusi tertinggi. Namun dalam dunia yang saling terhubung, kekuatan koersif tidak lagi membawa keamanan, melainkan kecemasan.
Apakah manusia benar-benar telah belajar dari dua perang dunia dan satu Perang Dingin, ataukah sejarah sekadar berganti kostum dengan nama baru? Mungkin benar, seperti yang disampaikan RAND (2024), bahwa kekuatan sejati abad ke-21 diukur bukan dari kemampuan menghancurkan, melainkan dari kemampuan menjaga stabilitas dalam keberagaman kepentingan.
Keputusan untuk menghidupkan kembali istilah “Department of War” adalah simbol politik yang mengguncang imajinasi global. Ia tidak serta-merta mengubah fungsi Pentagon, tetapi membuka kembali pertanyaan mendasar: bagaimana kekuatan besar seharusnya memaknai tanggung jawab globalnya? Bahasa adalah refleksi niat, dan niat membentuk tindakan. Di tengah dunia yang semakin rapuh oleh krisis kepercayaan, mungkin sudah saatnya kita berhati-hati pada setiap kata yang kita pilih karena satu kata saja dapat mengubah cara dunia memaknai keamanan.