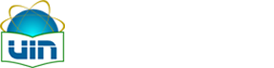Kecerdasan Buatan dan Bayangan Ancaman Baru bagi Keamanan Dunia
Penulis : Nadia Putri Khairani (Mahasiswa Hubungan Internasional)
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sedang mengubah wajah dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan ledakan pesat AI: mulai dari chatbot yang mampu menulis esai dan bahkan puisi, kendaraan tanpa supir, hingga drone tempur yang mampu beroperasi dengan sendirinya, menembak tanpa operator manusia. AI kini hadir dalam setiap aspek kehidupan. Teknologi ini menjanjikan efisiensi dan kemajuan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, di balik inovasi itu, terselip suatu kekhawatiran besar: apakah AI hadir membawa ‘berkah’ kemajuan, atau justru menjadi ancaman baru bagi keamanan nasional dan internasional?
AI dan Dinamika Keamanan Global
Secara historis, setiap lompatan teknologi selalu mengubah peta keamanan dunia. Dari penemuan mesiu, nuklir, hingga penemuan internet, semuanya membawa dua potensi kemungkinan, bagai pisau bermata dua, antara perlindungan dan kehancuran. Kini AI hadir dan menempati posisi yang jauh lebih kompleks.
Laporan PBB tahun 2024 menyebut bahwa lebih dari 30 negara telah mengembangkan sistem senjata berbasis AI, dan sebagian di antaranya bahkan tidak memerlukan kendali manusia langsung. Kondisi ini membuka resiko baru, perang yang dikendalikan algoritma teknologi, dan bukan murni putusan manusia. Selain itu, ancaman tidak datang hanya dari militer. Serangan siber berbasis AI dapat melumpuhkan infrastruktur penting seperti listrik, keuangan, atau komunikasi dalam hitungan detik. Di dunia maya, batas antara serangan dan ‘eksperimen teknologi’ menjadi kabur.
Selama dua dekade terakhir, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Uni Eropa berlomba mengembangkan teknologi AI. Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) tahun 2024 mencatat, investasi militer berbasis AI global telah menembus lebih dari 120 miliar dolar AS, dan terus diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya. AI kini menjadi elemen utama dalam sistem pertahanan, analisis intelijen, hingga perang siber. Drone otonom di medan tempur Ukraina dan Gaza misalnya, telah menunjukkan bagaimana keputusan mematikan bisa diambil tanpa kendali manusia. Resiko eskalasi konflik meningkat, karena kesalahan algoritma bisa memicu serangan otomatis yang tak terkendali.
Tak hanya di medan perang, AI juga digunakan untuk pengawasan massal, manipulasi informasi, dan propaganda digital. Teknologi deepfake mampu memalsukan video dan suara dengan tingkat akurasi tinggi, menciptakan ancaman baru terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik.
Ancaman terhadap Keamanan Nasional
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tantangan AI terletak pada bagaimana melakukan perlindungan terhadap kedaulatan digital. AI memang menjanjikan efisiensi serta kemandirian digital. Namun, di sisi lain, ia juga menciptakan digital dependency, dimana suatu negara menjadi bergantung pada teknologi asing, kepada data dan infrastruktur luar negeri.
Kebocoran data publik, manipulasi informasi, hingga penyalahgunaan AI untuk kampanye politik adalah bentuk ancaman yang semakin nyata. Isu keamanan nasional kini tidak lagi sebatas pertahanan fisik, tetapi juga perlindungan data dan algoritma yang memprosesnya.
Selain itu, ancaman ekonomi turut mengintai. Negara yang tertinggal dalam penguasaan teknologi AI berisiko menjadi pasar pasif bagi produk-produk algoritmik asing. Ketergantungan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga keamanan strategis—karena data warga negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan intelijen luar negeri. Oleh sebab itu, membangun AI sovereignty atau kedaulatan AI menjadi keharusan strategis, setara pentingnya dengan kedaulatan energi atau pangan.
AI dan Etika Global
Masalah lain muncul di tataran etika internasional. Negara-negara besar berlomba menciptakan AI yang “lebih cerdas”, tapi belum ada regulasi global yang mengikat penggunaannya. Hal ini tentu ini menimbulkan dilema moral: siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan fatal? Apakah pengembang, negara, atau algoritma itu sendiri?
Isu ini bahkan pernah dibahas dalam Konferensi Keamanan Munich 2025, di mana para diplomat memperingatkan risiko AI dalam geopolitik, di mana kekuatan algoritma bisa menentukan arah politik dan ekonomi dunia lebih dari diplomasi manusia.
Selain itu, AI memperlebar kesenjangan global antara negara maju dan negara berkembang. Negara dengan kemampuan riset, data, dan teknologi tinggi akan semakin dominan, sedangkan negara lain berisiko menjadi penonton. Fenomena ini menciptakan jurang baru yang menggantikan kesenjangan ekonomi tradisional.
Dalam konteks etika, dunia kini dihadapkan pada dilema: bagaimana menciptakan inovasi tanpa kehilangan kendali moral? Banyak kalangan menyerukan perlunya kerangka etik internasional yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penggunaan AI. Namun, konsensus global masih jauh dari kata tercapai.
Menjaga Keseimbangan antara Inovasi dan Keamanan
Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, dunia membutuhkan pendekatan baru terhadap AI, bukan sekedar menolak atau mendukungnya. Dunia internasional perlu mencari titik moderasi antara inovasi dan keamanan. AI seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya. Transparansi, kolaborasi global, dan literasi digital masyarakat menjadi kunci untuk memastikan AI bekerja bagi perdamaian, bukan ketakutan.
Namun, menjaga keseimbangan ini tidaklah mudah. Di satu sisi, negara-negara maju berlomba menciptakan inovasi AI untuk memenangkan kompetisi global. Di sisi lain, negara berkembang justru masih berjuang membangun regulasi dan kapasitas keamanan digital yang memadai. Ketimpangan teknologi ini menciptakan kerentanan yang tidak merata di antara negara. Ketika satu pihak memegang kendali atas teknologi canggih, pihak lain terancam menjadi pengguna pasif yang bergantung.
Selain itu, masalah keterbukaan juga jadi tantangan besar. Banyak sistem AI di dunia saat ini masih bersifat seperti “kotak hitam”, artinya cara kerja dan pengambilan keputusannya tidak benar-benar dipahami, bahkan oleh pembuatnya sendiri. Dalam hal keamanan, hal ini tentu berisiko. Bayangkan jika sistem pertahanan otomatis salah mengenali target, atau algoritmanya dimanipulasi untuk kepentingan politik dan ekonomi. Tanpa pengawasan yang jelas dan aturan yang tegas, AI bisa berubah menjadi “senjata tersembunyi” yang sulit dikendalikan manusia.
Karena itu, peran regulasi internasional menjadi sangat penting. Dunia membutuhkan semacam aturan global yang mengatur batasan penggunaan AI, terutama dalam konteks militer, politik, dan keamanan siber. PBB sebenarnya telah mulai membahas inisiatif semacam ini melalui Global Digital Compact, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang benar-benar mengikat. Negara-negara besar masih enggan tunduk pada regulasi global karena kepentingan strategis dan ekonomi yang sangat besar di balik AI.
Di tingkat nasional, pendekatan keamanan terhadap AI juga harus bersifat multidimensional. Tidak cukup hanya memperkuat infrastruktur digital, tetapi juga membangun digital ethics dan kesadaran publik. Literasi digital menjadi benteng pertama untuk melawan penyalahgunaan AI, baik dalam bentuk disinformasi, propaganda, maupun manipulasi data pribadi. Masyarakat perlu paham bahwa setiap interaksi dengan teknologi kini memiliki konsekuensi keamanan.
Lebih jauh, kerja sama antarnegara di bidang AI harus diarahkan pada nilai-nilai kemanusiaan. AI seharusnya memperkuat diplomasi, bukan memperlemah kepercayaan antarbangsa. Negara-negara dapat mengembangkan mekanisme pertukaran teknologi yang adil, riset bersama yang terbuka, dan sistem keamanan siber kolektif untuk mencegah perlombaan senjata digital. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan bersama perlu menjadi dasar dari tata kelola AI dunia yang baru.
Akhirnya, menjaga keseimbangan antara inovasi dan keamanan berarti menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kemajuan teknologi. Kecerdasan buatan tidak boleh mengaburkan nilai kemanusiaan yang menjadi inti dari perdamaian global. Teknologi hanya akan membawa manfaat jika dikelola dengan tanggung jawab dan kesadaran moral. Dalam dunia yang semakin diwarnai algoritma dan data, keputusan paling penting tetaplah milik manusia, bukan milik mesin.
Penutup: Teknologi Harus Tetap Manusiawi
AI adalah refleksi dari niat manusia di baliknya. Ia bisa menjadi alat untuk menciptakan perdamaian, tapi juga senjata yang memicu ketegangan baru. Keamanan dunia di masa depan mungkin tidak lagi ditentukan oleh jumlah pasukan atau rudal, melainkan oleh siapa yang menguasai algoritma, serta bagaimana algoritma itu digunakan.
Namun, di balik kecanggihan teknologi, ada satu hal yang tidak boleh hilang: nilai kemanusiaan. Teknologi, secerdas apa pun, tetap harus berpihak pada manusia. Tanpa arah moral dan kesadaran etis, kemajuan teknologi justru dapat menjerumuskan dunia ke dalam ketidakpastian baru. Kita tidak bisa hanya berfokus pada “apa yang bisa dilakukan AI”, tetapi harus mulai bertanya “apa yang seharusnya dilakukan AI.” Inilah batas etika yang menentukan apakah teknologi akan menjadi mitra bagi peradaban, atau ancaman bagi keberlanjutan umat manusia.
AI sejatinya hanyalah alat, bukan entitas yang memiliki niat atau moral. Tanggung jawab sepenuhnya tetap berada di tangan manusia: para ilmuwan, pengembang, pemimpin politik, dan masyarakat pengguna. Oleh karena itu, setiap langkah dalam pengembangan dan penerapan AI perlu didasari pada prinsip tanggung jawab sosial dan moral yang kuat. Transparansi dalam pengembangan, akuntabilitas dalam penerapan, dan perlindungan terhadap hak privasi manusia harus menjadi prioritas utama.
Kita perlu mengingat, sejarah selalu mencatat bahwa setiap revolusi teknologi membawa konsekuensi besar bagi kemanusiaan. Revolusi industri mengubah sistem ekonomi global, revolusi digital mengubah cara manusia berkomunikasi, dan kini revolusi AI berpotensi mengubah struktur kekuasaan dunia. Jika tidak dikelola dengan bijak, kecerdasan buatan bisa memperlebar ketimpangan antara negara kaya dan miskin, antara mereka yang mengendalikan teknologi dan mereka yang hanya menjadi pengguna. Ketimpangan ini pada akhirnya dapat menciptakan bentuk kolonialisme baru, kolonialisme digital—di mana kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh senjata, tetapi oleh data dan algoritma.
Oleh karena itu, penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia, untuk mengambil posisi aktif dalam membentuk arah kebijakan dan etika global terkait AI. Indonesia perlu membangun kemandirian digital, memperkuat keamanan siber, dan menanamkan nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan teknologi. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan agar pengguna tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga warga digital yang kritis dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, masa depan keamanan internasional akan bergantung pada kemampuan manusia untuk menyeimbangkan antara kemajuan dan kendali. Dunia membutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi destruktif. Teknologi AI seharusnya tidak menjadi perlombaan siapa yang paling cepat dan paling kuat, tetapi siapa yang paling bijak dalam menggunakannya.
Kecerdasan buatan mungkin bisa melampaui kemampuan manusia dalam hal kecepatan dan analisis, tetapi ia tidak akan pernah bisa menggantikan nurani, empati, dan moralitas yang hanya dimiliki manusia. Di tengah derasnya arus inovasi, manusia harus tetap menjadi pusat dari setiap keputusan dan arah perkembangan teknologi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa canggih mesin yang menentukan masa depan dunia, tetapi seberapa bijak manusia menggunakannya.