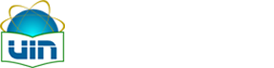Dunia yang Terserang oleh Nafasnya Sendiri
Penulis: Siti Zahra Afwan
Mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Saya percaya, dunia tidak perlu perang besar untuk belajar tentang rapuhnya peradaban. Kadang, cukup oleh satu virus yang tak terlihat, seluruh sistem global bisa lumpuh total. Covid-19 membuktikan bahwa keamanan internasional tidak selalu hancur karena bom, senjata, atau invasi, tapi juga karena satu hal kecil yang mengguncang napas manusia di seluruh dunia.
Pandemi ini jadi titik balik besar bagi cara kita memandang arti “keamanan”. Selama ini, keamanan internasional selalu digambarkan dalam konteks militer: perang, senjata, konflik antarnegara. Namun sejak 2020, semua konsep itu mendadak terasa sempit. Ketika virus menyebar, perbatasan negara tidak lagi berarti, militer tidak bisa menembak penyakit, dan teknologi senjata tidak bisa melawan ketakutan yang datang bersama setiap batuk.
Negara-negara besar yang selama ini jadi simbol kekuatan dunia justru terlihat paling panik. Amerika Serikat yang bangga dengan kekuatan militernya, kewalahan menghadapi lonjakan pasien. Eropa yang selalu bicara soal solidaritas, justru sibuk menutup diri. Dunia mendadak sadar bahwa senjata dan kekuasaan politik tidak menjamin keamanan karena yang paling dibutuhkan ternyata bukan tank atau misil, tapi masker, tenaga medis, dan sistem kesehatan yang kuat.
Pandemi mengubah arah pembicaraan tentang keamanan internasional. Kini, ancaman tidak hanya datang dari perang atau terorisme, tapi juga dari isu-isu non-tradisional seperti kesehatan global, keamanan pangan, perubahan iklim, dan bahkan kejahatan siber. Covid-19 menempatkan kesehatan sebagai bagian penting dari keamanan manusia (human security), yang menekankan kesejahteraan dan keselamatan individu, bukan sekadar kekuatan negara.
Bagi mahasiswa hubungan internasional, ini menarik. Karena pandemi bukan cuma peristiwa medis, tapi juga politik global. Negara-negara saling berlomba menunjukkan siapa yang paling siap, paling cepat menanggapi, atau bahkan paling berkuasa lewat vaksin. Muncul istilah baru — vaccine diplomacy — ketika vaksin jadi alat politik luar negeri. China, Amerika, dan Rusia memanfaatkan vaksin sebagai simbol pengaruh: siapa yang memberi, siapa yang bergantung.
Namun dibalik semua itu, ada ironi besar. Ketika negara-negara besar bersaing, jutaan warga di negara berkembang hanya bisa menunggu giliran. Ketimpangan distribusi vaksin menunjukkan kalau solidaritas global yang sering digaungkan di forum internasional ternyata rapuh. Dunia ini masih sangat egois bahkan dalam urusan menyelamatkan nyawa manusia.
Covid-19 bukan hanya menginfeksi tubuh, tapi juga cara berpikir manusia. Di awal pandemi, kita melihat solidaritas dan gotong royong tumbuh di mana-mana. Tapi semakin lama, rasa takut dan ego membuat banyak negara menutup diri. Dunia jadi seperti cermin: memperlihatkan wajah asli manusia ketika berada di bawah tekanan.
Negara-negara sibuk menyelamatkan diri sendiri, masyarakat mulai curiga satu sama lain, dan disinformasi menyebar lebih cepat daripada virus itu sendiri. Pandemi menunjukkan bahwa yang rapuh bukan cuma sistem kesehatan, tapi juga kepercayaan sosial. Di saat dunia seharusnya bersatu, justru muncul tembok-tembok baru bukan dari beton, tapi dari rasa tidak percaya.
Keamanan global akhirnya terasa seperti ilusi. Karena seaman-aman apapun sebuah negara, ia tetap bisa goyah oleh ancaman yang tidak kasat mata. Dan itu membuktikan bahwa keamanan bukan lagi tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling siap dan paling peduli.
Dunia pasca Covid-19 menghadapi babak baru dalam hubungan internasional. Pandemi telah memperlihatkan pentingnya diplomasi yang lebih manusiawi bukan sekadar hubungan antarnegara, tapi hubungan antarindividu. Negara-negara tidak lagi bisa hanya memikirkan kepentingan domestik tanpa melihat keterkaitan global yang begitu erat.
Krisis kesehatan kemarin menunjukkan bahwa apa yang terjadi di satu negara bisa dengan cepat berdampak ke seluruh dunia. Dari Wuhan ke New York, dari Jakarta ke Roma, virus berjalan lebih cepat daripada kebijakan. Karena itu, diplomasi di masa depan harus lebih responsif, lebih transparan, dan lebih kolaboratif.
Organisasi seperti WHO, PBB, dan ASEAN juga belajar dari kegagapan mereka di awal pandemi. WHO yang sempat dikritik karena terlambat memberi peringatan, kini berusaha memperkuat sistem peringatan dini. ASEAN yang dulu sibuk dengan isu ekonomi, kini mulai membahas kerjasama kesehatan regional. Semua ini membuktikan bahwa krisis besar memang menyakitkan, tapi juga membuka ruang perubahan.
Selain itu, pandemi mempercepat transformasi digital dalam diplomasi. Pertemuan internasional kini bisa dilakukan lewat layar, bukan meja konferensi. Diskusi global yang dulu terasa kaku kini lebih inklusif, karena batas ruang dan waktu mulai hilang. Tapi disisi lain, tantangan keamanan siber meningkat dari kebocoran data, propaganda digital, sampai manipulasi informasi yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri.
Bagi Indonesia sendiri, pandemi jadi momen refleksi. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk besar, Indonesia diuji kemampuan koordinasi dan solidaritasnya. Di sisi diplomasi, Indonesia aktif menyerukan kerja sama global dalam distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi. Pandemi jadi panggung untuk menunjukkan bahwa peran diplomasi tidak hanya tentang perjanjian, tapi tentang kemanusiaan.
Dunia pasca Covid-19 memaksa kita untuk menulis ulang makna keamanan internasional. Kini, keamanan berarti memastikan sistem kesehatan tangguh, membangun kolaborasi lintas negara, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi global seperti WHO. Keamanan juga berarti memastikan semua orang punya akses terhadap informasi dan fasilitas kesehatan karena tanpa itu, tidak ada stabilitas yang bisa bertahan lama.
Pandemi juga membuka kesadaran baru tentang pentingnya keamanan digital. Saat aktivitas manusia beralih ke ruang daring, ancaman siber meningkat drastis. Banyak negara mulai memperkuat perlindungan data dan sistem online mereka, karena serangan siber kini dianggap sama berbahayanya dengan serangan militer.
Di sisi lain, pandemi juga menumbuhkan empati baru. Dunia menyadari bahwa krisis global tidak bisa diselesaikan sendirian. Negara kaya butuh negara berkembang, negara besar butuh kerja sama kecil, dan semua manusia tanpa melihat bendera, butuh satu sama lain.
Covid-19 memang meninggalkan luka, tapi juga pelajaran. Ia mengingatkan kita bahwa konsep keamanan internasional tidak bisa lagi dilihat dari kekuatan militer atau ekonomi semata. Keamanan sejati adalah kemampuan untuk menjaga kehidupan manusia, baik secara fisik, sosial, maupun emosional.
Mungkin, pandemi sudah lewat. Tapi pelajaran darinya seharusnya tidak ikut hilang. Karena dunia yang pernah berhenti hanya untuk menarik nafas seharusnya kini tahu betapa berharganya satu tarikan nafas itu.
Ke depan, keamanan global tidak lagi bisa dibangun dengan senjata, tapi dengan solidaritas. Tidak cukup dengan batas negara, tapi dengan empati. Karena kalau pandemi kemarin mengajarkan sesuatu, itu adalah kenyataan bahwa musuh terbesar manusia bukan virus… tapi ketidakpedulian.