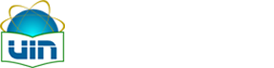Departemen “Perang”: Sinyal Baru Amerika Serikat yang Mengusik Tatanan Dunia
Penulis : Sania Adilla Putri, Ilmu Hubungan Internasional
Ketika sebuah kekuatan besar seperti Amerika Serikat secara resmi mengubah nama dan peran salah satu institusinya dari “Departemen Pertahanan” menjadi “Departemen Perang”, kita tak boleh hanya melihatnya sebagai pergantian kata atau label birokrasi saja. Lebih dari itu, langkah ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa perubahan paradigma bisa mengguncang tatanan keamanan internasional yang selama ini relatif stabil.
Meski kelihatannya prosedural, wacana semacam itu sudah cukup menimbulkan kegelisahan. Bagaimana jika Amerika Serikatbukan lagi dipersepsikan sebagai penjaga perdamaian dunia, melainkan sebagai aktor yang berpotensi memicu ketegangan dan eskalasi konflik lintas kawasan?
Dari “Pertahanan” ke “Perang”: Makna Strategis di Balik Istilah
Pada 5 September 2025, Presiden Donald J. Trump menandatangani sebuah executive order untuk mengembalikan nama Departemen Perang sebagai gelar sekunder bagi Departemen Pertahanan AS. Dalam dokumen resmi disebutkan bahwa instansi boleh menggunakan gelar seperti Secretary of War, Department of War, dan Deputy Secretary of War dalam korespondensi resmi, komunikasi publik, upacara, dan dokumen non-statutori lainnya.
Namun, penting dicatat bahwa secara legal nama Departemen Pertahanan tetap tertulis dalam undang-undang AS, karena perubahan tersebut memerlukan persetujuan Kongres. Mengapa hal ini penting? Karena bahasa menciptakan persepsi, dan persepsi mempengaruhi perilaku negara di arena internasional. Kata “pertahanan” membawa nuansa bahwa militer adalah alat terakhir yang digunakan ketika diplomasi gagal. Sedangkan kata “perang” membawa aura ofensif, yang menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer bukan opsional tetapi tersentral.
Dalam perspektif teori hubungan internasional, khsusunya realisme ofensif, kekuatan besar tidak hanya mempertahankan dirinya, tetapi secara aktif memperluas pengaruh dan kekuatannya jika diperlukan. Jika label Departmen Perang digunakan, maka hal itu mempertegas bahwa AS siap menggunakan militernya sebagai instrumen utama dalam kebijakan luar negeri.
Aliansi & Sistem Keamanan dalam Bayang-Bayang “Perang”
Salah satu dampak paling signifikan dari langkah ini adalah pada struktur aliansi internasional yang selama ini dipimpin oleh AS seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan kerjasama di kawasan Indo-Pasifik seperti AUKUS dan QUAD. Sekutu mungkin mulai melihat bahwa aliansi mereka bukan semata untuk perlindungan bersama, tetapi bisa berubah menjadi mekanisme ekspansi militer bersama.
Aliansi yang sejak lama dibangun atas argumen pertahanan kolektif bisa berubah makna, bukan lagi “kita saling melindungi jika diserang”, tetapi “kita bersama-sama menyerang jika diperlukan”. Ini tentu menimbulkan keraguan di kalangan mitra bahwa mereka terlibat dalam agenda ofensif yang bukan semata untuk stabilitas, melainkan untuk mendikte perubahan kekuasaan.
Sementara itu, negara lain yang bukan sekutu seperti Tiongkok dan Rusia akan melihat langkah ini sebagai kesempatan memperkuat narasi bahwa AS adalah kekuatan hegemonik yang agresif, bukan sekedar pelindung.
Krisis Norma & Rezim Keamanan Global
Sistem keamanan global yang dibangun pasca Perang Dunia II didasarkan pada prinsip kolektivitas, kontrol penggunaan kekuatan militer, dan penghindaran konflik besar antarnegara. Ini tercermin dalam organ seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), traktat senjata, dan mekanisme diplomasi multilateral. Ketika sebuah kekuatan besar seperti AS secara institusional menormalisasi penggunaan kekuatan militer melalui label “perang”, maka kredibilitas seluruh rezim ini bisa tergoyahkan. Negara lain bisa meniru pendekatan serupa, merasa bahwa jika hegemon utama menggunakan kekuatan sebagai instrumen utama, maka mereka pun hak untuk melakukan hal yang sama.
Dengan demikian, norma bahwa “perang adalah pilihan terakhir” berubah menjadi “perang adalah salah satu pilihan utama”. Tren ini bisa memunculkan eskalasi militer yang lebih cepat, erosi kontrol senjata, dan melemahnya lembaga internasional yang selama ini berfungsi sebagai penahan konflik. Lebih jauh lagi, tantangan abad 21 seperti perubahan iklim krisis pangan, pandemi, dan cyber menuntut kerjasama global, bukan peningkatan militerisasi. Jika sumber daya muncul paradoks bahwa dunia semakin bersenjata ketika yang paling dibutuhkan adalah saling berbagi dan bekerjasama.
Realisme vs. Kebutuhan Tata Dunia Baru
Langkah Amerika Serikat bisa dibaca sebagai bentuk kemmbalinya politik kekuasaan klasik (power politics) di tengah krisis legitimasi global. Namun, pendekatan tersebut semakin tidak relevan di era ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, pandemi, dan disrupsi teknologi. Alih-alih memperkuat keamanan, militerisasi justru mengalihkan sumber daya dari isu-isu global yang lebih mendesak.
Selain itu, kebijakan ini mencerminkan paradoks keamanan (security paradox), bahwa semakin sebuah negara memperkuat militernya untuk menciptakan rasa aman, semakin tidak aman dunia secara keseluruhan. Amerika Serikat yang selama ini memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas global, kini justru memperkuat persepsi kekuatan dan kecurigaan antarnegara.
Dari perspektif konstruktivisme, tindakan ini juga membentuk ulang identitas internasional Amerika Serikat. Istilah “Departemen Perang” tidak hanya merefleksikan kebijakan luar negeri yang agresif, tetapi juga membangun citra bahwa kekuatan militer kembali menjadi simbol identitas nasional. Padahal sejak akhir Perang Dingin, Amerika Serikat mencoba menampilkan dirinya sebagai promotor perdamaian dan demokrasi global.
Respon Dunia dan Tantangan bagi Global South
Langkah Amerika Serikat dalam mengubah istilah “Departemen Pertahanan” menjadi “Departemen Perang” memicu beragam reaksi. Di Eropa, para pemimpin politik saat ini menghadapi dilema antara menjaga loyalitas terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan merespons kekhawatiran publik yang cenderung menolak militerisasi berlebihan. Uni Eropa yang selama ini menekankan pendekatan doplomatik dan rules-based order kini dihadapkan pada tekanan untuk menegaskan strategic autonomy, yaitu kemampuan mempertahankan keamanan regional tanpa sepenuhnya bergantung pada Washington.
Meskipun sebagian negara seperti Polandia atau Inggris mungkin tetap mendukung kebijakan militer Amerika Serikat, negara seperti Jerman dan Prancis cenderung bersikap hati-hati agar tidak terseret dalam agenda yang mereka anggap ofensif. Di sisi lain, bagi negara anggota ASEAN, munculnya istilah “Departemen Perang” bersinggungan dengan prinsip ASEAN Way yang mengutamakan dialog, konsensus, dan non-intervensi.
Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura kini harus menavigasi hubungan strategis dengan Amerika Serikat tanpa kehilangan citra netralitas regional. Dalam konteks yang lebih luas, Global South berisiko semakin terpinggirkan jika rivalitas kekuatan besar kembali mendominasi panggung internasional. Ketika sumber daya global diarahkan pada perlombaan senjata, isu-isu fundamental seperti kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi justru terabaikan.
Refleksi dan Kesimpulan: Apakah Ini Ancaman Internasional?
Perubahan nama institusi memang tampak sepele, tetapi dalam politik global, simbol kecil bisa melahirkan konsekuensi besar. Dunia tidak lagi melihat Amerika sebagai pelindung tatanan internasional, tetapi mulai mencurigainya sebagai sumber ketegangan baru.
Secara simbolik, Amerika Serikat mengirim pesan bahwa perang bukan lagi sesuatu yang dihindari, tetapi dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, negara-negara lain akan memperkuat pertahanan dan mencurigai setiap gerakan Amerika Serikat, yang bisa memicu perlombaan senjata baru. Serta, secara strategis tindakan ini dapat memperlemah norma internasional tentang penggunaan kekuatan, membuka jalan bagi justifikasi agresi oleh negara lain.
Jika Amerika Serikat memilih “Departemen Perang” di dunia yang seharusnya memperjuangkan perdamaian, maka bukan hanya wajah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berubah, tetapi juga arah masa depan dunia. Karena ketika kekuatan terbesar mulai mendefinisikan dirinya melalui perang, maka seluruh tatanan keamanan internasional berada dalam ambang krisis yang mengancam kestabilan global.