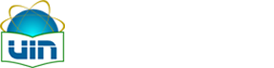Antara Fiksi dan Ancaman: Mengurai Isu Keamanan di Balik Bendera Bajak Laut One Piece
Penulis : Khaerina Iqlima (Mahasiswa Hubungan Internasional)
Belakangan ini muncul di dunia maya mengenai simbol-simbol fiksi yang dianggap dapat memicu konflik atau ancaman terhadap keamanan internasional, salah satunya adalah bendera bajak laut dari serial One Piece. Bendera yang menampilkan tengkorak dengan topi jerami itu dianggap sebagian orang sebagai simbol kekerasan, pemberontakan, dan perampokan. Namun, benarkah simbol fiksi semacam ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan dunia nyata?
Aksi demonstrasi yang terjadi saat itu, ketika seorang pengemudi ojek online terluka setelah dilindas oleh aparat. Kejadian tersebut menjadi meningkatnya eskalasi kemarahan publik, hingga akhirnya massa mulai menyusun 17 + 8 tuntutan rakyat sebagai simbol kegelisahan bahwa suara rakyat selama ini tidak benar-benar didengar. Di arus tersebut, terlihat sebuah simbol yang tak biasa menarik perhatian publik hingga media internasional yaitu bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari serial anime One Piece kian marak di Indonesia menjelang peringatan HUT RI ke-80. Bendera hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami ini merupakan simbol kelompok bajak laut fiksi yang dipimpin oleh tokoh utama anime tersebut. Simbol ini jelas bukan Merah Putih. Ia bukan lambang resmi negara, melainkan representasi budaya pop fiksi.
Pengibaran bendera ini tentunya memicu perdebatan serius di ruang publik dan media sosial. Sebagian masyarakat memanfaatkan simbol ini untuk menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah dan sebagian lainnya sebagai bentuk perlawanan atas kondisi sosial dan politik saat ini. Di sisi lain, aksi tersebut sangat memicu kontroversi yang luas, terutama dari pemerintah. Namun seiring kemunculannya justru memicu perdebatan yaitu sebagian kalangan menganggap pengibaran simbol tersebut sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap bendera kebangsaan dan nilai-nilai para pahlawan.
Ketika Bahasa Politik Berubah, tetapi Negara Masih Membaca dengan Kamus Lama
Generasi hari ini tidak lagi selalu menggunakan spanduk panjang atau jargon ideologis. Mereka berbicara melalui simbol budaya pop seperti meme, anime, musik dan film. Bagi mereka, Bendera One Piece bukan hanya lambang negara tandingan, tetapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang merujuk pada cerita dan narasi dalam anime tersebut seperti pemerintah dunia yang korup, rakyat yang tertindas, dan sosok bajak laut yang melawan demi martabat manusia. Hal ini sangat mempresentasikan situasi pemerintah Indonesia saat ini. Maka dari itu, bendera itu dipilih karena relevan dan bukan karena hendak menggantikan bendera merah putih. Ia bukan simbol penolakan terhadap NKRI, tetapi sebagai simbol keberanian moral terhadap kekuasaan yang dianggap tuli. Permasalahan dalam hal ini merujuk pada pemerintah dan sebagian publik yang konservatif membaca simbol tersebut dengan logika “selain merah putih sama dengan ancaman” padahal bagi generasi muda, simbol ekspresi itu tidak tunggal dan tidak berarti nasionalis.
Saya berpendapat bahwa pengibaran bendera One Piece bukanlah bentuk mendahulukan merah putih, melainkan bentuk depresi rakyat ketika kata-kata tidak didengar dan simbol negara hanya dimiliki oleh negara, bukan oleh rakyat. Ini bukan sekedar kritik visual, tetapi sinyal bahwa rakyat mencari bahasa baru untuk didengar karena bahasa lama tidak lagi efektif. Menghadapi fenomena ini, langkah yang bijak itu bukan memburu siapa yang membawa bendera anime, tetapi bertanya mengapa simbol fiksi terasa lebih relevan dibanding simbol negara hari ini.
Apakah Situasi ini Mengancam Keamanan Internasional?
Secara objektif, pengibaran bendera One Piece dalam demonstrasi tidak serta masuk kategori ancaman keamanan internasional karena tidak ada indikasi mobilisasi kekuatan bersenjata lintas negara, tidak ada jejaring teroris global dan tidak ada proyek ideologi transnasional terorganisasi seperti yang terjadi pada ISIS atau Al-Qaeda.
Namun, dari perspektif human security dan political stability, fenomena ini memberi sinyal yang perlu diperhatikan secara serius oleh komunitas global. Bukan karena simbolnya, tetapi karena tingkat frustasi rakyat terhadap negara sudah mencapai titik di mana ekspresi politik tidak lagi percaya pada simbol formal negara. Kondisi semacam ini dikategorikan sebagai warning sign yaitu kegagalan negara untuk mengelola kepercayaan publik hingga memicu destabilisasi politik domestik yang pada titik ekstrim dapat berdampak regional, terutama jika menyentuh sektor ekonomi, teknologi, atau geopolitik digital. Dengan kata lain, bukan bendera One Piece yang mengancam keamanan internasional tetapi negara terus gagal membaca bahasa rakyatnya sendiri dan inilah yang berpotensi menjadi masalah global.
Pengibaran bendera One Piece tidak secara inheren mengancam keamanan internasional, tetapi di Indonesia ada pandangan yang menganggapnya provokatif dan melanggar hukum karena dianggap merendahkan simbol negara dan berpotensi memprovokasi masyarakat
Representasi Simbol Menjadi Bahasa Politik Baru
Fenomena ini mengindikasikan pergeseran mendasar dalam cara generasi muda bernegosiasi dengan kekuasaan. Jika pada era Reformasi 1998 bahasa yang digunakan adalah retorika ideologis dan mobilisasi fisik, namun kini bentuk perlawanan berkemabang menjadi jauh lebih naratif, simbolik, dan kultural. Simbol-simbol fiksi bukan lagi sekedar bentuk hiburan, melainkan artikulatif ketika demokrasi formal dirasa tidak lagi efektif. Generasi saat ini tidak lagi merasa perlu menggunakan bahasa negara untuk mengkritik suatu negara. Mereka membangun semesta dan narasi mereka sendiri, lalu mengundang negara untuk menjawabnya. Hal inilah yang membuat bentuk-bentuk simbolik seperti bendera One Piece menjadi wacana serius bukan karena destruktifnya, melainkan karena kemampuannya yang menjadi cermin retak bagi legitimasi negara. Representasi simbol dalam politik kontemporer tidak lagi bersifat ornamental, tetapi menjadi bahasa utama untuk menegosiasikan kekuasaan. Bukan pidato, bukan manifesto, melainkan simbol visual yang memiliki resonansi emosional dan kultural. Ini menandakan bahwa politik hari ini bergerak dari logika argumentatif menuju logika afektif yang di mana rasa lebih kuat daripada kata.
Cerita One Piece dengan tokoh sentral, Monkey D. Luffy dan para krunya menjadi agensi dalam melawan kekuatan-kekuatan opresif yang menimbulkan ketidakadilan. Problematikanya pun seputar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kesenjangan sosial dan ekonomi, penindasan, hingga gejala otoritarianisme. Dalam hal ini sangat merepresentasikan apa yang sedang terjadi di Indonesia dan juga beberapa negara lain.
Adapun salah satu perwakilan komunitas One Piece Indonesia itu mengatakan bahwa pengibaran bendera ini hanyalah sebagai aksi simbolis dari bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah., Aksi tersebut memang bukalah ajakan untuk pemberontakan. Seorang akademisi sosilog juga berpendapat bahwa pengibaran bendera yang dilakukan oleh sejumlah warga juga tidak seharusnya perlu direspons secara berlebihan oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa pengibaran bendera ini juga sebagai bentuk ekspresi politik dan sosial bagi generasi muda, karena mereka cenderung menggunakan simbol budaya populer untuk menyuarakan keresahan apa yang dialami oleh masyarakat. Selama lima tahun terakhir pula, hampir semua kritik dan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah itu diwujudkan lewat simbol tertentu, seperti Garuda Biru saat aksi Indonesia Gelap. Dalam hal ini simbol-simbol tersebut tentunya mencerminkan kritik dan perlawanan masyarakat terhadap pemerintah.
Saat Keberanian Rakyat Indonesia Menyulut Gelombang Perlawanan Regional
Hal menarik dari demonstrasi pada Agustus lalu bukan hanya skalanya, tetapi dampak psikologis yang ditimbulkannya di luar negeri. Meskipun media dalam negeri hampir tidak meliput aksi tersebut, justru media internasional yang meliput fenomena tersebut secara langsung dan intens. Sorotan itu akhirnya membuat demonstrasi Indonesia tidak hanya menjadi peristiwa politik nasional tetapi memicu pergerakan dari negara lain.
Di Filipina, Thailand, hingga Malaysia diskursus publik di media sosial menunjukkan bahwa keberanian rakyat Indonesia menjadi inspirasi nyata bagi masyarakat mereka untuk ikut berani menggugat pemerintahnya sendiri. Bukan karena tuntutan mereka sama, tetapi karena mereka melihat Indonesia berhasil menembus tembok ketakutan yang selama ini membatasi suara rakyat. Fenomena serupa juga terlihat ketika para pemuda di Nepal turun ke jalan bulan lalu untuk memprotes gaya hidup mewah para elit politik, hingga akhirnya mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan. Simbol ini juga berkibar di berbagai negara Afrika, seperti dalam protes di Madagaskar yang melawan kelangkaan air dan listrik, serta di Maroko yang memprotes buruknya layanan kesehatan. Seorang pengunjuk rasa di Madagaskar itu mengatakan bahwa kaum muda merasa tidak didengar oleh pemerintah dan terjebak dalam sistem, ia mengatakan “Selain hiburan, bajak laut Topi Jerami melambangkan kebebasan, kemerdekaan semangat yang Anda miliki untuk menentang otoritas yang tidak adil. Itu sangat menginspirasi saya”.
Sebelumnya, para demonstran di Hong Kong menggunakan Pepe the Frog, di Myanmar menggunakan hormat tiga jari dari “The Hunger Games”, dan di tempat lain topeng Guy Fawkes dari “V For Vendetta” yang juga menjadi simbol perlawanan. Dari fenomena tersebut, yang lebih mengejutkan dari seluruh gelombang protes ini adalah kenyataan bahwa yang menggugah keberanian lintas negara bukanlah simbol budaya populer. Pengibaran bendera One Piece menjadi bukti bahwa generasi hari ini tidak lagi membutuhkan manifesto untuk melawan, tetapi mereka menciptakan bahasanya sendiri.
Krisis Legitimasi dan Evolusi Demokrasi
Fenomena ini sebetulnya menandai sebuah babak baru dalam demokrasi: rakyat tidak lagi meminta ruang, tetapi menciptakan ruang mereka sendiri. Jika negara hanya merespons simbol secara represif tanpa membongkar pesan yang terkandung di dalamnya, maka yang terancam bukan keamanan nasional, melainkan legitimasi politik. Karena yang tengah dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas, tetapi kepercayaan. ini menempatkan kita pada sebuah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara hari ini masih sepenuhnya memahami rakyatnya? Sebab yang sedang terjadi bukan hanya demonstrasi, melainkan tanda bahwa model demokrasi prosedural mulai kehilangan relevansi di mata generasi baru. Demokrasi yang hanya berdiri pada pondasi pemilu, hukum tertulis, dan jargon stabilitas kini dianggap dangkal, karena gagal menyentuh lapisan terdalam dari demokrasi: pengakuan terhadap rasa dan martabat manusia.
Krisis ini bukan soal stabilitas keamanan, melainkan relasi negara-warga. Demokrasi tidak runtuh karena amarah, melainkan karena negara gagal mengakui kemarahan sebagai komunikasi terakhir. Langkah strategis bukan hanya mempersempit ekspresi, melainkan menerjemahkan bahasa baru rakyat melalui diplomasi domestik yang empatik dan adaptif.
Reaksi Negara: Antara Melindungi Simbol dan Mengabaikan Aspirasi
Respons pemerintah terhadap fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas yang kontraproduktif karena negara tampak lebih cepat bereaksi terhadap bentuk ekspresi, ketiimbang substansi aspirasi. Fokus pemerintah yang menilai pengibaran bendera fiksi sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap Merah Putih yang justru memperlihat bahwa negara masih terjebak pada pemahaman simbol sebagai atribut seremonial, bukan sebagai komunikasi politik. Paradoks ini memperlihatkan jarak pemahaman antara negara dan warganya. Saat rakyat berbicara melalui simbol karena pintu dialog formal dirasa tertutup, pemerintah justru merespons simbol tersebut sebagai ancaman ketertiban, bukan sebagai permintaan untuk didengar. Alih-alih menafsir simbol sebagai sinyal peringatan dari rakyat, pemerintah justru memperlakukannya sebagai gangguan terhadap wibawa negara.
Banyak pejabat publik yang menganggap bahwa fenomena ini sebagai ancaman karena dianggap berpotensi memecah belah bangsa dan mengancam persatuan. Mereka pun menganggap bahwa hal ini dinilai melanggar aturan hukum penghormatan terhadap bendera negara karena seharusnya masyarakat menghargai pengorbanan para pejuang dan pahlawan yang telah berkorban untuk menghormati bendera merah putih dari hasil perjuangan kolektif para pendahulu dan juga tidak mudah untuk memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa. Padahal dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan bahwa Pengibaran bendera itu tidak dilarang selama tidak lebih tinggi atau lebih besar dari bendera Merah Putih. Pada fenomena ini banyak kasus bahwa posisi bendera One Piece itu tetap berada di bawah Merah Putih.
Dalam logika ini, negara tampak lebih sibuk mempertahankan citra, daripada memahami rasa. Padahal, demokrasi modern tidak cukup dijaga melalui regulasi dan wibawa, melainkan harus dirawat melalui legitimasi emosional yakni keyakinan rakyat bahwa suara mereka benar-benar diakui dan dihargai. Keterlambatan negara untuk memahami makna di balik simbol ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keamanan nasional sedang dipahami secara sempit, sebatas ancaman fisik dan bukan ancaman terhadap legitimasi. Padahal yang paling berbahaya bagi negara bukanlah bendera fiksi, melainkan ketika rakyat merasa negara tidak lagi relevan untuk diajak bicara.
Negara Harus Belajar Mendengar, Bukan Hanya Mengatur
Krisis yang dihadapi bukan semata soal stabilitas keamanan, tetapi krisis relasi antara negara dan warga negara. Demokrasi tidak runtuh karena amarah rakyat, melainkan karena negara gagal mengakui bahwa kemarahan itu adalah bentuk komunikasi terakhir yang tersisa. Di titik ini, langkah yang paling strategis bukan mempersempit ruang ekspresi, melainkan menerjemahkan bahasa baru rakyat.
Pendekatan keamanan yang terlalu normatif hanya akan melahirkan ketegangan baru. Justru negara perlu bergeser ke diplomasi domestik yang lebih empatik dan adaptif. Negara yang cerdas bukan hanya yang mampu bertahan dari kritik, tetapi yang mampu bertumbuh karena mendengar bahkan ketika rakyat memilih berbicara melalui simbol fiksi, bukan pidato formal.
Hari ini, bendera bajak laut dari serial anime telah berkibar di jalanan Indonesia. Besok, mungkin simbol berbeda yang muncul. Namun satu hal yang jelas yaitu ketika rakyat merasa merasa tak lagi diperdengarkan oleh struktur yang resmi, mereka akan mencari cara sendiri untuk berbicara dan simbol budaya pop bisa menjadi alat untuk menyuarakan hak mereka. Kita sebagai pengamat, mahasiswa, atau pemerhati sosial-politik bukan sekedar menyaksikan atau mengecam tetapi mendengarkan.
Mendengarkan suara yang terwakilkan dalam bendera fiksi dalam sorak massa dalam simbol yang dulu dianggap main-main. Karena ketika negara gagal membaca bahasa generasi yang menuntut keadilan dengan cara baru, bukan hanya stabilitas yang terancam tetapi legitimasi yang menjadi modal bersama pun turut longgar. Mari kita pastikan bahwa simbol-simbol yang muncul di jalanan bukanlah tanda kegagalan warga, tetapi peringatan bagi negara untuk benar-benar hadir dan mendengar.